NARASIBARU.COM - Ketika seorang calon kepala daerah mengantongi dukungan besar dan berjuang merebut kursi eksekutif.
Satu hal yang kerap terlupakan adalah biaya politik yang harus dibayar.
Di Provinsi Riau, kasus OTT yang menjerat Gubernur Abdul Wahid akhirnya menampakkan.
bahwa proyek-anggaran di pemerintahan daerah bisa berubah menjadi jalur pembayaran balik modal politik.
Menurut keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Skema yang dipakai adalah penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Yang kemudian dibagi sebagian ke kepala daerah “semacam jatah preman sekian persen”, ungkap juru bicara KPK.
Beberapa pakar menilai bahwa modal kampanye yang mahal memunculkan kebutuhan untuk “balik modal” setelah pejabat terpilih.
Dengan kontrol anggaran yang besar di tingkat daerah, posisi gubernur atau bupati menjadi sangat strategis tidak hanya untuk pelayanan publik.
Tetapi juga untuk potensi businessman dalam proyek publik.
Dalam kasus Riau, KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang senilai sekitar Rp 1,6 miliar.
Sebagai indikasi bahwa aliran dana bukan sekadar satu kali, tetapi bagian dari rangkaian pembayaran.
Praktik ini menunjukkan bahwa kursi gubernur di Riau bukan hanya jabatan publik, tapi juga investasi politik yang harus segera menghasilkan “imbal hasil”.
Gubernur yang terpilih, secara teoritis, adalah pelayan publik.
Tapi ketika kursi itu juga berfungsi sebagai pengusaha proyek, maka batas antara kepentingan publik dan pribadi menjadi kabur.
Sumber KPK mengungkap bahwa dalam skema ini, pejabat daerah menetapkan prosentase “jatah” dari anggaran proyek untuk disetor ke atasannya.
Singkatnya pejabat daerah, seperti gubernur, menjadi titik akhir transaksi proyek, bukan sebagai pengawas publik.
Tetapi sebagai pihak yang menerima return dari proyek yang dikelola.
Skema ini berdampak buruk bagi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Uang yang semestinya untuk pembangunan infrastruktur maju terbagi sebagai biaya tersembunyi, dan kualitas proyek bisa menurun.
Apalagi jika motivasi proyek berubah dari kebutuhan publik menjadi pengembalian investasi politik.
Di sisi demokrasi, hal ini menciptakan siklus pejabat yang terpilih bukan dengan visi pelayanan, tetapi dengan ambisi modal balik.
Akibatnya, partisipasi publik dan integritas pemerintahan daerah menjadi korupsi sistemik, bukan kejadian tunggal.
Untuk mematahkan skema “pengusaha proyek” ini, reformasi perlu menyasar beberapa titik kritis:
Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye supaya pejabat tak terlilit utang politik yang kemudian dibayar melalui proyek.
Pengawasan internal pemerintah daerah yang lebih kuat, independen, dan rutin—terutama pengadaan barang dan jasa serta UPT-nya.
Pendidikan integritas di tingkat lokal agar pejabat memahami bahwa jabatan bukanlah hak eksploitasi, melainkan amanah publik.
Kasus Gubernur Abdul Wahid di Riau bukan sekadar tajuk berita kriminalitas.
Ia adalah sinyal bahwa kepala daerah bisa menjadi pengusaha proyek tersembunyi, menjalankan skema pembayaran balik modal politik dengan mengorbankan publik.
Sampai sistem kampanye, penganggaran, dan pengawasan berubah.
Maka kursi pemerintahan daerah tetap akan menjadi arena pengembalian investasi politik, bukan semata tempat untuk melayani rakyat. (*)










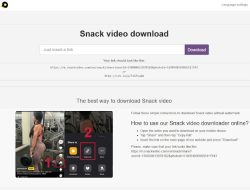
Artikel Terkait
Usai Tersangkakan Nadiem, Nurcahyo Jabat Kajati Kalteng
Akhir Pelarian Anggota Resmob ‘Abal Abal’, Tipu Ratusan Ternyata Buat Ini
Ira Puspadewi Tak Bisa Disamakan dengan Tom Lembong
Anak Riza Chalid soal Kasus Minyak Mentah: Ayah Saya Tak Terlibat!